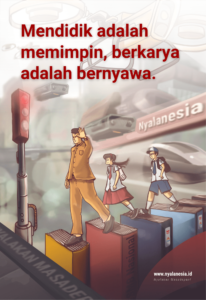Akulturasi merupakan perpaduan antara komponen-komponen budaya yang berbeda dan bersatu dalam usaha membentuk kebudayaan baru tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan yang asli (Setyaningsih, 2020). Di Indonesia, negara dengan keragaman etnis dan budaya yang sangat kaya, proses akulturasi ini sangat jelas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kuliner. Salah satu contoh menarik dari fenomena akulturasi budaya ini adalah semangkuk grombyang, sebuah hidangan khas dari Pemalang Jawa Tengah yang mengalami berbagai perubahan seiring dengan waktu dan pengaruh budaya lain.
Isi dalam semangkuk grombyang adalah sup daging yang memiliki karakteristik dan cita rasa khas, hasil dari proses akulturasi yang melibatkan berbagai pengaruh dari luar dan dalam negeri. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana proses akulturasi budaya mempengaruhi semangkuk grombyang, mengidentifikasi elemen-elemen budaya yang terlibat, serta menganalisis dampak dari akulturasi ini terhadap masyarakat dan budaya lokal. Grombyang tidak hanya sekedar kuliner yang disantap saat lapar, tetapi di dalamnya ada rincian sejarah, komponen budaya, serta tantangan dan peluang sehingga kuliner khas Pemalang ini perlu untuk dilestarikan.
Grombyang adalah makanan yang mirip dengan soto dengan isian yang berbeda yang berisi irisan daging kerbau yang berkuah hitam pekat dengan bahan baku berupa lada hitam dan rempah-rempah dengan penyajian antara isi dan kuahnya lebih banyak sehingga grombyang- grombyang (goyang-goyang) dan biasanya disajikan dalam mangkuk kecil dan dilengkapi dengan sate kerbau. Ciri khas lainnya dari nasi grombyang terletak pada tempat dagangannya yang berupa kuali akbar, tempat nasi ditutupi dengan kain merah. Belum diketahui siapa pertama kali yang menciptakan nasi grombyang. Namun konon kuliner asli dari Pemalang ini telah ada sejak 1960-an (Damayanti,et.al,2022).
Penamaan Makanan Grombyang sebagai Kuliner Tradisional Jawa dapat dilihat dari suku kata pembentuk penamaan makanan. Bahasa Jawa dominan menggunakan dua suku kata pada tiap kata dasarnya, selebihnya merupakan perluasan dari kata tersebut. Demikian halnya dengan nama makanan, tidak ada yang hanya terdiri atas satu silabe atau terdiri atas lebih dari dua silabe (Handayani, et.al, 2018). Penamaan grombyang memiliki dua suku kata yaitu [grom] dan [byang], dari penggunaan dua suku kata pada penamaan grombyang menunjukkan bahwa penamaan tersebut menunjukan makanan gromyang merupakan kuliner Jawa.
Makanan tradisional tidak hanya dibuat untuk menghilangkan rasa lapar. Selain itu, makanan tradisional juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Indonesia dan merupakan bagian dari masyarakat di suatu daerah tertentu (Lestari, et.al 2023). Dikutip dari jatengprov.go.id, sejak 29 Oktober 2021 grombyang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) oleh Kementerian dan Kebudayaan RI.
Nasi Grombyang adalah makanan yang mirip dengan soto dengan isian yang berbeda yang berisi irisan daging kerbau yang berkuah hitam pekat dengan bahan baku berupa lada hitam dan rempah-rempah dengan penyajian antara isi dan kuahnya lebih banyak sehingga grombyang-grombyang (goyang-goyang). Ramuan nasi grombyang terdiri dari nasi, irisan daging kerbau dan kuah, disajikan dalam mangkuk kecil dan dilengkapi dengan sate kerbau (Bintoro, et.al. 2022).
Bahan – bahan yang dibutuh dalam pembuatan Nasi Grombyang adalah sebagai berikut : Beras, Daging/jeroan kerbau atau sapi, Laos, Jahe, Kemiri, Bawang merah, Bawang Putih, Kunir, Pala, Ketumbar, Serai, Daun Salam, Merica, Gula Merah, Kelapa parut yang disangrai/Srundeng, dan Tauco. Semua bahan kecuali nasi, daging/jeroan dan kelapa diolah jadi satu dalam bentuk kasar dan halus.
Konsumen grombyang pada awalnya menupakan masyarakat Chinese, sehingga dapat dimaknai jika penggunaan tauco untuk menyesuaikan lidah konsumen yang didominasi oleh masyarakat pecinan Pemalang. Sedangkan tauco yang tergolong dalam bumbu utama grombyang merupakan bumbu masakan di Indonesia yang mendapat pengaruh kuliner China (warisan budaya Kemendikbud). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Pemalang merupakan masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan etnis lain, dalam hal ini adalah China. Penggunaan tauco pada grombyang sebagai simbol hidup berdampingan dan berbaur dengan etnis lain.
Keberadaan grombyang memunculkan nilai-nilai pada masyarakat yang meliputi nilai toleransi akulturasi. Penggunaan daging kerbau dipresentasikan sebagai akulturasi keagamaan pada zaman dahulu. Daging kerbau dimaknai sebagai simbol toleransi, di mana penggunaan daging kerbau juga digunakan pada soto Kudus. Penggunaan kerbau di Kudus sebagai bentuk toleransi (warisan budaya Kemendikbud). Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa grombyang yang menggunakan daging kerbau sebagai simbol adanya upaya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.
Penggunaan kerbau pada grombyang bukan hanya pada isian kuah saja, tetapi juga dalam bentuk sate. Meski disebut sebagai sate kerbau, tapi dari penyajiannya tidak tampak dibakar seperti sate pada umumnya. Hanya saja setelah daging dibumbui dan diungkep kemudian ditusuki seperti sate. Dalam penyajiannya sate ini dibalut dengan bumbu kelapa sangrai parut yang pekat. Kalau kurang pedas, tinggal ditambah cabai rawit rebus. Rasanya sedikit manis dan lembut di lidah karena diracik bersama kuah dengan ramuan bumbu khusus.
Jika kita menilik lebih jauh pernak-pernik pendamping soto, kita pun menemukan betapa kaya dan kosmopolitannya perjumpaan bumbu dalam sesajian ini. Kita melihat pengaruh Eropa ternyata juga hadir dalam kuah soto ini seperti ketumbar. Pernak-Pernik soto dan evolusi rombong pikulan ini bisa jadi sebagian besar terpengaruh dari pikulan para pedagang Cina sejak zaman baheula (Handayani, et.al, 2018). Pengaruh Eropa pada grombyang ada pada pilihan bumbu berupa ketumbar. Sedangkan pada penggunaan pikulan, akulturasi budaya Cina pada makanan ini nampak terlihat nyata. Dan saat ini, meskipun grombyang tidak lagi dijual dengan cara dipikul, pikulan masih digunakan oleh para pedagang grombyang.
Hal ini menunjukkan bahwa medernitas tidak serta merta menghilangkan tradisi budaya. Meskipun semangkok grombyang merupakan hidangan tradisional, perjalanan sejarahnya mencerminkan interaksi yang kompleks antara berbagai budaya. Ini merupakan bentuk akulturasi budaya asing ke dalam tradisi kuliner lokal. Proses akulturasi ini menciptakan kombinasi rasa yang harmonis antara pengaruh asing dan tradisi lokal.
Meskipun pengaruh asing memiliki dampak signifikan, elemen-elemen budaya lokal juga berperan penting dalam membentuk semangkok grombyang. Penggunaan bahan lokal seperti bawang, serai, daun salam, dan cabai mencerminkan adaptasi lokal.
Dalam hal rasa makanan masakan masyarakat Jawa Tengah cenderung lebih manis. Manisnya makanan juga ada kemungkinan terkait erat dengan karakter masyarakat Jawa Tengah yang memilih untuk berbaik hati, berbicara sopan santun, dan mengindari konflik dengan siapa pun. Intinya, bersikap manis. Dengan kata lain, ada kemungkinan rasa manis inilah yang menuntun masyarakat Jawa Tengah untuk bersikap “manis” (dalam arti kias) dalam hidupnya (Handayani, et.al, 2018).
Grombyang yang memiliki rasa cenderung manis ada keterkaitannya dengan karakter masyarakat Jawa yang berhati baik, berbicara sopan santun, dan menghindari konflik dengan siapa pun. Dalam kuliner grombyang ada tambahan bumbu berupa tauco sebagai bentuk kebaikan hati kepada etnis China, sedangkan penggunaan daging kerbau sebagai wujud toleransi beragama dengan agama lain. Sikap yang mencerminkan masyarkat Jawa ini, juga ini menjadi tanda bahwa masyarakat Pemalang memiliki rasa hormat terhadap apa yang menjadi kepercayaan agama lain.
Semangkok grombyang tidak hanya merupakan hidangan tetapi juga memiliki peran sosial budaya yang signifikan. Hidangan ini sering disajikan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, perayaan, dan pertemuan keluarga. Ini mencerminkan nilai-nilai komunitas dan hubungan sosial yang kuat dalam budaya Jawa.
Selain itu, semangkok grombyang juga menjadi simbol kekayaan kuliner dan identitas budaya. Dalam konteks ini, proses akulturasi tidak hanya mempengaruhi rasa dan teknik memasak tetapi juga cara hidangan ini dipersepsikan dan dihargai oleh masyarakat.
Proses akulturasi dalam semangkok grombyang memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan budaya lokal. Dampak ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk identitas budaya, ekonomi, dan pelestarian budaya.
Akulturasi budaya melalui semangkok grombyang memperkuat identitas budaya masyarakat Jawa Tengah. Integrasi elemen-elemen dari berbagai budaya menciptakan bentuk kuliner yang unik dan khas, yang menjadi bagian penting dari warisan budaya lokal. Semangkok grombyang, dengan semua pengaruh dan adaptasinya, mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi dan memadukan elemen-elemen asing ke dalam tradisi mereka sendiri.
Hidangan ini juga memperkuat keterhubungan komunitas. Semangkok grombyang sering disajikan dalam konteks sosial yang melibatkan keluarga dan teman-teman, menciptakan kesempatan untuk berbagi dan memperkuat hubungan sosial. Proses memasak dan menyajikan hidangan ini menjadi bagian dari praktik sosial yang memperkuat rasa kebersamaan dan identitas komunitas.
Semangkok grombyang memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam konteks pariwisata kuliner. Popularitas hidangan ini menarik perhatian wisatawan yang tertarik untuk mengalami cita rasa autentik dari kuliner Pemalang. Restoran dan warung yang menyajikan grombyang menjadi daya tarik bagi pengunjung dan berkontribusi pada industri pariwisata lokal.
Dampak ekonomi juga terlihat dalam penciptaan lapangan kerja dan dukungan terhadap ekonomi lokal. Pengrajin bumbu, petani rempah, dan pemilik restoran semuanya berkontribusi pada ekosistem ekonomi yang dinamis di sekitar gerombyang. Proses akulturasi ini membantu menghidupkan kembali ekonomi lokal dan mempromosikan produk lokal.
Meskipun akulturasi budaya membawa banyak manfaat, ada tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah risiko homogenisasi budaya, di mana elemen-elemen tradisional dapat tergerus oleh pengaruh modern dan globalisasi. Untuk menjaga keaslian grombyang, penting untuk terus mempromosikan dan melestarikan tradisi kuliner ini.
Upaya pelestarian melibatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga keanekaragaman budaya dalam kuliner. Inisiatif lokal, seperti festival makanan tradisional dan program pelatihan untuk generasi muda, dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa grombyang terus dihargai dan dipertahankan. Dukungan dari masyarakat dan pemerintah juga penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi kuliner ini.
Akulturasi budaya dalam semangkok grombyang adalah contoh nyata dari bagaimana elemen-elemen budaya yang berbeda dapat saling mempengaruhi dan berintegrasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan unik. Proses ini mencerminkan dinamika budaya yang kompleks di Indonesia, di mana berbagai pengaruh dari luar negeri dan lokal berpadu untuk membentuk warisan kuliner yang kaya dan beragam.
Dari pengaruh kuliner Cina, Eropa, maupun kepercayaan agama tertentu, hingga adaptasi dengan tradisi lokal, semangkok grombyang menunjukkan bagaimana budaya dapat berkembang melalui interaksi dan penyesuaian. Hidangan ini tidak hanya mencerminkan keanekaragaman budaya tetapi juga memperkuat identitas komunitas dan mendukung ekonomi
DAFTAR PUSTAKA
Bintoro, V. P., Rizqiati, H., & Nurwantoro, N. (2022). Upaya Peningkatan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Teknologi Continuous Sealer Untuk Mengemas Bumbu Grombyang Di Umkm Bumbu Grombyang Bintang Pemalang. Inisiatif: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(1), 14-17.
Damayanti, D., Wulandari, S. D., Fauziah, M. N., & Adinugraha, H. H. (2022). Pelatihan Pelayanan Prima Terhadap Warung Makan Nasi Grombyang Pemalang. Piramida: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1), 1-8.
Handayani, P. M., Arifin, Z., & Prayogi, I. (2018). Fenomena Grafem< E> Pada Penyebutan Nama Makanan Tradisional di Jawa Sebagai Karakter Budaya Indonesia.
https://jatengprov.go.id/beritaopd/masuk-warisan-budaya-ini-keistimewaan-nasi-grombyang-pemalang/
Lestari, N. K., Rahmanita, M., & Ingkadjaya, R. (2023). COTO MANGKASARA SEBAGAI MAKANAN TRADISIONAL DAN IDENTITAS DAERAH KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN. Jurnal Industri Pariwisata, 5(2), 163-169.
Setyaningsih, R. (2020). Akulturasi budaya jawa sebagai strategi dakwah. Ri’ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan, 5(01), 73-82.